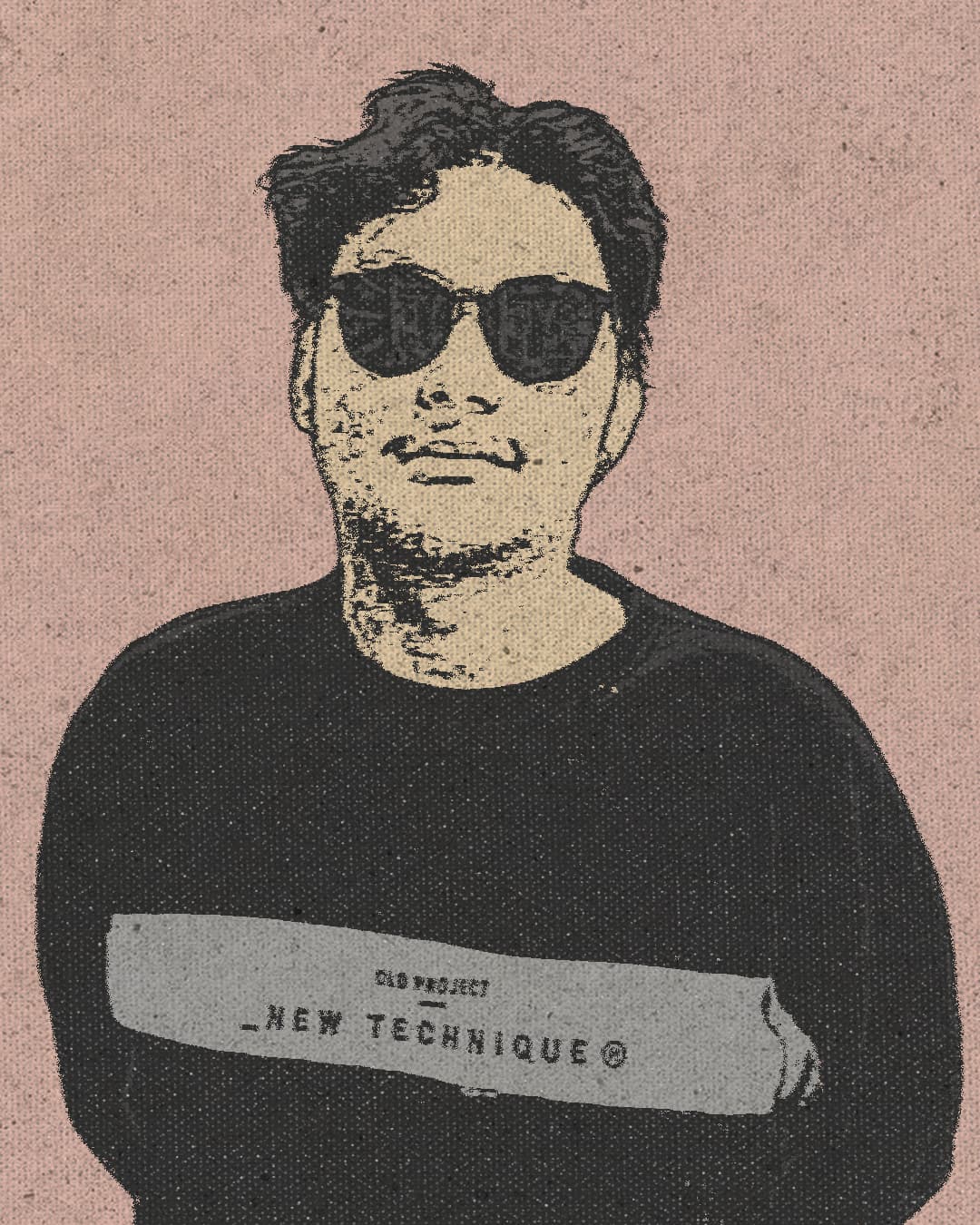ihwal.co – Di dalam mobil buatan Jepang yang disupiri W.S. Djambak, kami berlima akan menempuh perjalanan 58,6 km ke barat, menuju Bangkinang.
Saya benar-benar tidak sabar meninggalkan Pekanbaru yang madani, bertuah, runyam lagi berisik.
Tapi alasan utama ketidaksabaran saya adalah panas berdengkang yang mendera kota ini, seolah khusus untuk kami, Tuhan menetapkan satu matahari untuk setiap kepala.
Dan bagi penyair kere seperti saya, yang jangankan berbuat untuk bahasa dan bangsa, untuk membeli pendingin buatan saja saya jauh dari kata mampu, perjalanan ini adalah ihwal yang menggembirakan.
Apalagi Bangkinang merupakan kawasan di mana angin dataran tinggi merangkak turun dan angin pesisir memanjat naik saling bertemu dan menciptakan iklim hutan hujan tropis (Af), sehingga lebih layak dihuni manusia ketimbang Pekanbaru.
Dengan khidmat mobil buatan Jepang yang ban belakangnya agak kempes dan botak terus melaju dengan kecepatan sedang; melewati satu per satu truk-truk roda tiga belas yang memuat kayu balak hasil merambah hutan, anak-anak yang digotong ibunya mengutip hal-hal buruk yang dihasilkan sebuah kota, rimba yang didatarkan atas nama pembangunan, pamflet-pamflet politikus yang berdebu, dan seterusnya dan seterusnya. Pemandangan yang itu-itu juga.
Dalam perjalanan melewati itu semua, saya membayangkan diri saya adalah Thomas Dias yang pada tahun 1683 melakukan perjalanan ke pedalaman tinggi Sumatra, dan W.S. Djambak adalah Hendrik Temmer yang memimpin ekspedisi itu demi mencapai kesepakatan dagang dengan petinggi-petinggi pedalaman Sumatra.
Sebab kami pun begitu, akan menjumpai petinggi-petinggi post-kontemper wilayah pedalaman Sumatra Tengah, namun berbeda dengan Dias, alasan kami lebih adiluhung: spiritualitas.
Sesampainya di Bangkinang, tidak seperti Dias yang mula-mula ditolak oleh datuk-datuk kaum matrilineal di masa lampau, kami justru disambut dengan hangat.
Hangat sekali. Mungkin karena kami tidak berlagak sebagaimana tentara masuk kota, tapi serupa biksu dan biksuni dari dataran asing yang mengunjungi Muara Takus seribuan tahun lalu.
Dan, sebelum mempercakapkan hal-hal yang akan mengerutkan kulit di Warkop Rindang; literasi dan segala yang berkelindan di dalamnya, kami dijamu terlebih dahulu di pujasera.
Dengan sigap, saya pun memesan makanan yang menurut konvensi orang Indonesia dapat mengenyangkan: yang ada nasinya.
Tidak menunggu lama, pesanan saya datang, begitu juga pesanan kawanan saya yang sama-sama berangkat dari Pekanbaru.
Tanpa basa-basi, di samping potret maskulin beberapa intelektual Indonesia yang terlukis di dinding pujasera beserta quote terbaik mereka, segera saya lahap makanan itu.
Saat makanan saya tersisa beberapa suap sendok lagi, kira-kira tiga belas meter dari jarak saya makan, mata saya tertuju pada seorang anak yang terduduk sendirian di bawah dasbor lampu lalu lintas dan langit malam, di mana kendaraan berhenti dan berjalan setiap dua menit.
Dari ukuran tubuhnya, ia mungkin baru berusia sepuluh tahun, dan di sebelahnya termangu karung dua puluh kilo yang diisi barang-barang bekas.
Setelah selesai makan, dan orang-orang mulai berkemas menuju Warkop Rindang. Karena saya penasaran dengan bocah itu, maka saya mengajak Pram berjalan kaki, ketimbang naik mobil, padahal jaraknya cukup melelahkan untuk ditempuh dua betis lesu orang kota.
Untungnya Pram setuju, dan karenanya saya punya kekuatan menolak ajakan Djambak naik mobil.
Ketika saya lewat persis di depannya, bocah itu sama sekali tidak mengalihkan pandang. Ia sibuk menggerakkan sepeda mainan dengan kedua tangannya yang mungil.
Ingin saya duduk di sampingnya barang sekejap. Melihat apa yang dilihat matanya, mendengar apa yang ia dengar, atau lebih jauh, masuk ke dalam sesuatu yang tengah ia gumamkan.
Tapi saya terlalu pengecut, bahkan untuk sekedar menyapa. Saya takut kehadiran saya justru memperburuk setiap hal yang sedang ia rasakan.
Apalagi kalau saya sampai menjejalinya pertanyaan-pertanyaan yang penuh belas-kasih palsu khas orang kota yang merasa dirinya lebih mulia dari bocah mungil itu.
Jadi saya, begitupun Pram, terus melangkahkan kaki menuju Rindang, meninggalkan bocah itu dengan imajinya seorang diri.
Percapakan di Rindang berlangsung seru, kami saling melepas-tangkap wacana yang seharusnya tidak ditujukan untuk hal-hal yang dapat dilebur waktu, termasuk manusia: membicarakan arah kebudayaan, dan sastra pasca-kolonial.
Selain itu, kami juga membincangkan program-program yang akan kami kerjakan ke depannya untuk memberi warna baru bagi kawasan yang kadung punya tabiat mempernis lantai lapuk keagungan masa lalu demi secuil anggaran …
Angin lembah berkisiur, membawa udara dingin dataran tinggi ke puncak ubun kami, tapi percakapan berlangsung semakin hangat.
Kalau bukanlah karena Siti Salmah dan Ana adalah perempuan, juga seorang ibu, di mana jam malam mereka terbatas, percakapan pasti akan terus dilanjutkan lebih larut.
Namun bagaimanapun juga, untuk menenggang keterbatasan dua perempuan itu, kami harus kembali ke Pekanbaru; ke kota yang panas berdengkang dan lasak. Kota yang mungkin suatu hari nanti, akan dilalui lelaki bermata satu yang dinubuatkan tiga agama samawi.
Lelaki yang dalam perjalanannya dibekali banyak kekayaan, yang dengan kekayaan itu, ia barangkali akan ditepung-tawari juga oleh sekaum orang bertanjak, sebagaimana pejabat tinggi republik ini ditepung-tawari. Waw.
*Andreas Mazland: Lahir di Banda Aceh. Menulis di berbagai media. Bergiat di Mazhab Panam. Emerging Balige Writers Festival, Borubudur Writers Festival, dan Payakumbuh Writers Festival dan festival sastra lainnya. Selain menulis, Andreas Mazland adalah Pengamat Kebijakan Nuklir, Pakar Sejarah Tumbuh-tumbuhan, dan Penyair Kamar Mandi.