Beberapa hari lalu, ketika meninggalkan Panam menuju Bangkinang, saya tertegun melewati Simpang Kubu. Ingatan saya terulur menuju beberapa waktu silam yang tidak begitu jauh rentang waktunya.
Dulu setiap kali melewati daerah ini, selalu berhasil menyita perhatian saya. Betapa tidak, di daerah Riau ini, menemukan sawah serupa di depan halaman rumah ibu saya merupakan sebuah pemandangan langka, dan itu saya jumpai di sini.
Bentangan sawah, kerbau yang merumput, dan bangau yang melumpur, mampu mengobati kerinduan saya terhadap kampung halaman.

Namun, kali ini saya tidak bisa menutupi keterkejutan saya melihat sawah itu ditimbun alat berat serupa mengubur jasad. Yang lebih mengejutkan lagi, tak jauh dari sawah itu, sebuah bukit dibelah serupa cake ulang tahun.
Beberapa puluh meter tak jauh dari sana, masih sejalur jalan raya menuju Bangkinang, saya melihat pemandangan sejenis. Sebuah rawa ditimbun dan diratakan, entah apa tujuannya.
Alih fungsi lahan ini amat meresahkan saya. Kehilangan tutupan hutan membuat asupan oksigen semakin menipis. Demikian juga kehilangan komunitas rawa turut berperan penting dalam menyimpan karbon.
Belum lagi meningkatnya produksi gas rumah kaca membuat panas matahari terperangkap dalam lapisan ozon yang serupa kubah tak terlihat.
Akhirnya saya bisa memahami kenapa belakangan ini Riau semakin panas, seakan masing-masing orang memiliki matahari di atas ubun-ubunnya—setidaknya kurun sepuluh tahun terakhir.

Jika ditilik, kira-kira dari mana akar masalah semua ini bermula?
Asumsi saya pribadi, jauh sebelum ritel menjamur dan ruko berserakan serupa panu pada punggung kerbau, pokok permasalahannya terjadi ketika kita mulai tumbuh sebagai Bangsa Indonesia.
Sebagai negara yang berkembang dan tergila-gila akan modernisasi, kita mencoba mengadopsi seluruh pengetahuan moderen tanpa mengadaptasinya, serta melupakan akar budaya nusantara.
Pembangunan yang mengedepankan “ego” (kedirian) memunggungi aspek penting “eko” (lingkungan), digalakkan hanya demi mengejar kata kesejahteraan semu.
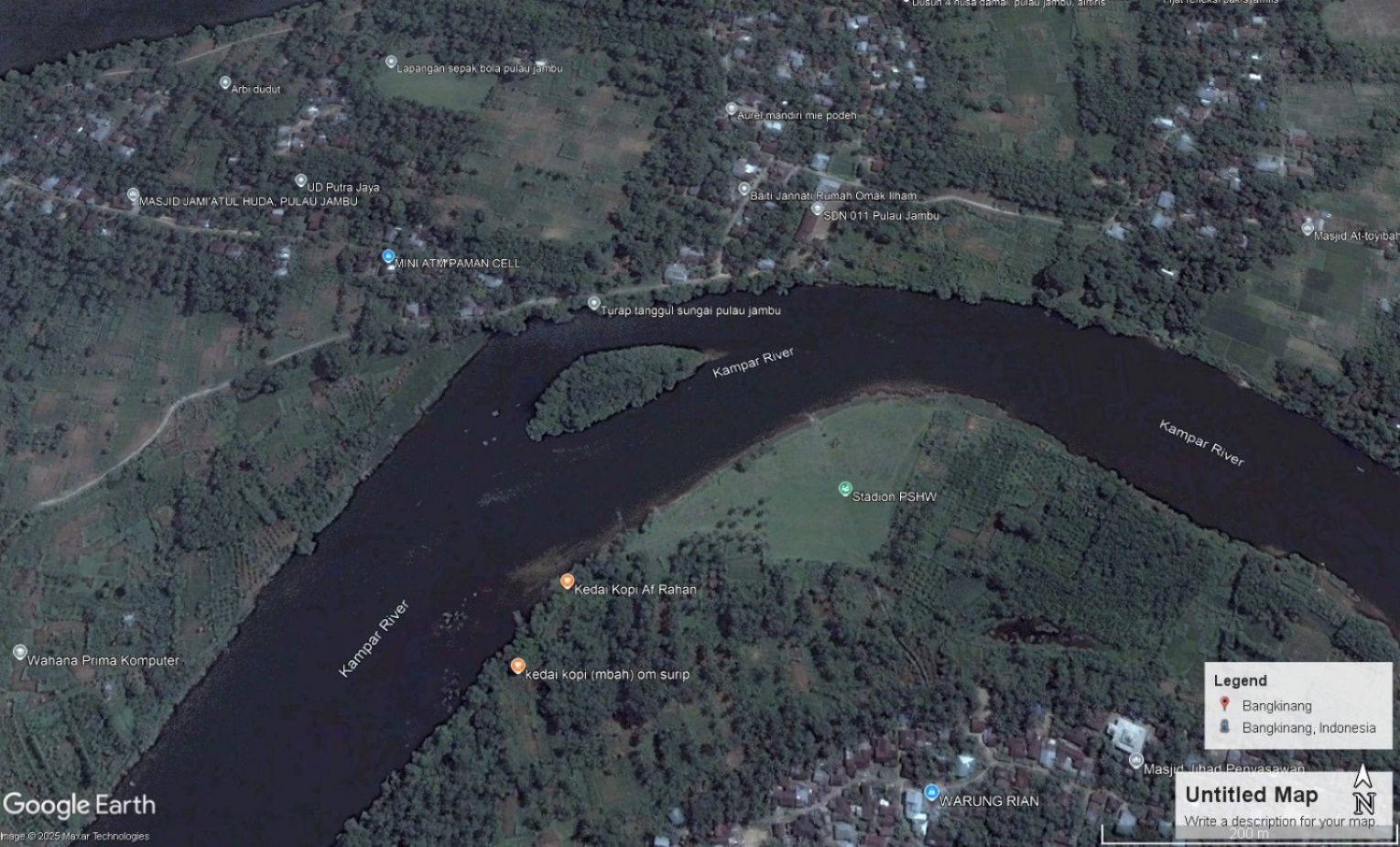
Eksploitasi dengan dalih peningkatan ekonomi terjadi di mana-mana dan berujung terjadinya bencana. Tak berhenti di situ saja, pemerintah kita kerap menampilkan tontonan akrobatik dalam menangani bencana yang seringkali justru membuat persoalan semakin pelik. Bak lain sakit, lain diobat, pemerintah kerap gagap dan latah pada saat bersamaan.
Ketika masalah muncul, mereka tergagap, sehingga untuk menutupinya, kerap mengeluarkan komentar yang (tidak) lucu—yang memunculkan reaksi publik. Sadar akan tindakannya yang garing—dan tentu saja karena telanjur viral—kemudian mereka kembali muncul sebagai Inspektur Vijay pada filem India dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan latah.
Gagap dan latah ini membuat kita ditertawakan dunia sebagai pemain sirkus lingkungan. Fenomena ini membuat saya teringat kutipan lama, “Panem et circences”.

Setali tiga uang, media arus utama yang seharusnya berperan dalam mengontrol pemerintah melalui pengarahan opini publik, justru lebih tertarik memberitakan urusan selangkangan para pejabat ketimbang pengrusakan lingkungan. Hal ini yang membuat permasalahan ekologis di Indonesia demikian buruk.
Bisa dimaklumi, sebab, media yang tetap harus mencari pemasukan melalui rating tontonan, harus mengutamakan selera pasar. Dan masyarakat kita memang kebanyakan tidak memiliki ketertarikan terhadap lingkungan—selain daripada gosip murahan. Tak berlebihan jika disebut bahwa sebagai sebuah pohon, kita sudah busuk dari akar hingga ke ujung batang. Sehingga jikalau boleh, saya menyebutnya sebagai egosistem, alih-alih ekosistem.
Lantas, siapa yang patut disalahkan? Apakah Nasida Ria karena lagu Tahun 2000-nya? Atau Cucu Cahyati dengan Bumi Semakin Panas-nya?

Kerusakan terjadi di mana-mana, dan kita tetap saja memperparah dengan kerusakan lainnya. Sampai kapan kita bersikap egois, sok modernis yang meninggalkan sikap hidup harmonis dengan alam yang diajarkan oleh nenek moyang kita?
Malahan mencibirnya sebagai pengetahuan tradisional yang tertinggal. Sawah diganti ruko, bungkus pisang diganti plastik.
Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal, dan konflik dengan manusia semakin pelik. Kebijakan transmigrasi, serta industri perkebunan alih-alih pertanian, membuat mimpi buruk ini entah kapan berakhirnya—yang jika didedahkan satu demi satu, tentu tidak akan cukup satu purnama.
Pengetahuan lawas dari leluhur seakan terputus, dan kita kembali mengemasi jejak ingatan kolektif masa lalu yang berserakan. Yang tertimbun di dalam pondasi ruko, yang tergerus ekskavator, dan dihanyutkan aliran limbah hingga ke hilir.
Kita yang kelabakan pada masa ini memang terkaget dengan realita dan mencoba untuk merevitalisasi alam yang sudah telanjur rusak.
Ya, biasanya konservasi memang dimulai dengan melihat realita saat ini, dan mengenang masa lalu, serta mencemaskan kejadian beberapa tahun lagi yang semakin tidak jelas.

Lucunya, seakan belum kapok dengan modernisasi, bahkan upaya konservasi dilakukan dengan mengadopsi ilmu yang diperoleh dari pengetahuan moderen. Padahal, jauh sebelum bernama Indonesia, masyarakat adat kita sudah sangat memahami apa itu konservasi.
Mereka bisa menjadikan alam yang terkembang menjadi guru. Bersahabat dengan bencana secara bersahaja—yang dikenal sebagai mitigasi dan adaptasi dalam ilmu pengetahuan moderen.
Misalkan, mengapa rumah adat kita kebanyakan rumah panggung? Atau mengapa dulu nenek moyang kita menerapkan sistem pertanian berpindah? Atau juga mengapa dulu menggunakan alat tangkap bubu, alih-alih racun?
Atau jika mengabaikan cibiran Tan Malaka perihal logika mistika, mengapa keberadaan harimau dianggap sebagai sosok penting seperti keberadaan ninik mamak bagi kita masyarakat pedalaman Sumatra?
Tentu ada alasan kuat yang barangkali belum mampu kita terjemahkan menggunakan ilmu pengetahuan moderen membuat kita dengan pongahnya melabeli pengetahuan tradisional tersebut sebagai kajian metafisika atau mitos belaka.
Sadar akan hebatnya pengetahuan lama, atau mungkin karena kerisauan budaya, negara kita mulai kembali mencoba merangkul masyarakat adat dengan pengakuan setengah hatinya terhadap keberadaan masyarakat adat. Salah satu prasyaratnya adalah adanya sebuah lembaga yang mengurusi adat, peradatan, dan peradaban masyarakat adat.
Hal ini cukup menggembirakan, mengingat adanya kesadaran kolektif untuk kembali ke pangkal. Namun ternyata, permasalahan belumlah selesai hingga di sini. Kesadaran budaya dan ekologis yang hipokrit itu ternyata berujung pada pengrusakan yang semakin menakutkan.
Jika dulu musuh dari masyarakat adalah kapitalis, sekarang muncul musuh yang selama ini berselimut dalam selimut yang sama. Ibaratkan tongkat yang membawa rebah. Masyarakat dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi kepentingan mereka. Entah itu pemuka adat, atau bahkan pemerintah sendiri.
Sebut saja kasus perambahan hutan adat di Desa Balung, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, seluas 6.000 hektar. Atau pengrusakan alam di Raja Ampat, Karanganyar, dan berbagai tempat lainnya—yang katanya memiliki izin.

Jika ada yang melempar sebuah pertanyaan besar, apakah alam bisa pulih kembali, maka dengan pesimistis, saya hanya bisa berkata, “Jangan kebanyakan bermimpi. Lipat selimut dan mulai bekerja. Kita masih harus mencari makan. Hidup ini terlalu pantek, dan kita dipaksa menikmatinya.” [*]
*Windi Syahrian a.k.a. WS. Djambak, merupakan seorang Penulis Negeri Sipil yang menjabat sebagai Peneliti Ahli Madya di Laboratorium Sastra Mazhab Panam. Memiliki spesialisasi keahlian di bidang psikologi persampahan, antropozoologi, astrobiologi, dan berbagai bidang pseudosains lainnya. Seorang penganut paham bumi tidak bulat, dan tidak datar, melainkan merupakan salah satu percabangan pohon. Saat ini sedang merampungkan sebuah tulisan tidak ilmiah yang ditargetkan terbit pada jurnal terindeks scopus.







